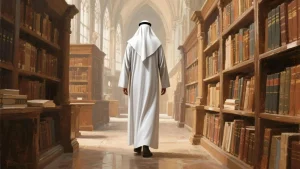Jembatan Dua Zaman: Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari sebagai Solusi Tantangan Era Digital
- 15 July 2025
- Oleh Redaksi Santri Bangkit

Pendahuluan
Latar Belakang
Era digital telah menghadirkan perubahan fundamental dalam cara manusia berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bahkan dalam cara mereka memahami realitas. Teknologi informasi yang berkembang pesat telah membawa kemudahan dan kemajuan yang signifikan, namun juga memunculkan berbagai tantangan baru: krisis identitas, polarisasi masyarakat, penyebaran hoaks, radikalisme daring, hingga erosi nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.
Dalam konteks ini, warisan intelektual dan spiritual dari para ulama Nusantara menjadi relevan untuk digali kembali. Salah satu tokoh yang pemikirannya menawarkan perspektif mencerahkan adalah Hadrotus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari (1871-1947). Sebagai pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan pengasuh Pesantren Tebuireng, KH. Hasyim Asy’ari telah meninggalkan jejak pemikiran yang bukan hanya mendalam secara spiritual, tetapi juga visioner dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Meskipun hidup pada era yang jauh berbeda, prinsip-prinsip yang diletakkan oleh KH. Hasyim Asy’ari mengandung nilai universal yang dapat diterjemahkan dalam konteks kekinian. Moderatisme Islam yang menjadi ciri khas pemikirannya, penekanan pada adab dalam pencarian ilmu, keseimbangan antara menjaga tradisi dan keterbukaan terhadap pembaruan, serta komitmen pada persatuan umat—semua ini menawarkan perspektif segar dalam menghadapi kompleksitas era digital.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah:
- Bagaimana relevansi prinsip-prinsip keilmuan dan etika pencarian ilmu yang diajarkan KH. Hasyim Asy’ari dalam konteks dunia digital yang dipenuhi informasi tanpa batas?
- Bagaimana konsep pendidikan berbasis akhlak dan karakter yang digagas KH. Hasyim Asy’ari dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan di era digital?
- Bagaimana perspektif KH. Hasyim Asy’ari tentang komitmen terhadap tradisi dan kearifan lokal dapat dikontekstualisasikan dalam era globalisasi digital?
- Dalam konteks kekinian, bagaimana pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang peran ulama dan nasionalisme dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata di ruang digital?
Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini yaitu:
- Menganalisis dan mengeksplorasi relevansi pemikiran KH. Hasyim Asy’ari dalam menjawab tantangan era digital, terutama dalam aspek keilmuan, etika, pendidikan, dan sosial keagamaan.
- Mengidentifikasi nilai-nilai universal dari pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang dapat menjadi panduan bagi generasi muslim dalam menavigasi kompleksitas dunia digital.
- Memberikan kontribusi pada diskursus akademis tentang integrasi nilai- nilai Islam tradisional dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.
- Memperkaya khazanah studi tentang pemikiran ulama Nusantara dan relevansinya dalam konteks global dan kontemporer.
Pembahasan
Keteladanan dalam Keilmuan dan Keikhlasan
Hadrotus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari merupakan figur ulama yang tidak hanya dikenal karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena keteladanan dalam sikap dan pengamalan nilai-nilai keilmuan. Dalam kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim, beliau memaparkan secara komprehensif tentang etika yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu maupun pengajar ilmu (Dhofier, 2011). Menurut Khuluq (2018), konsep adab yang diusung oleh KH. Hasyim Asy’ari bukan sekadar formalitas, melainkan inti dari proses keilmuan itu sendiri.
Relevansi pemikiran ini sangat signifikan di era digital. Menurut penelitian Rahmawati dan Baroroh (2020), masyarakat digital saat ini menghadapi krisis literasi yang ditandai dengan melimpahnya informasi namun minimnya kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan menyaring informasi secara kritis. Qomar (2019) menyatakan bahwa kasus-kasus penyebaran hoaks dan disinformasi yang marak terjadi di media sosial merupakan indikasi dari absennya nilai etika dan kebenaran dalam proses transmisi informasi. Prinsip tabayyun (verifikasi) yang ditekankan dalam ajaran Islam menjadi sangat relevan.
Menurut KH. Hasyim Asy’ari, etika mencari ilmu perlu memperhatikan verifikasi, otentikasi, dan menghormati otoritas keilmuan tulis (Zuhri, 2021). Pandangan ini sejalan dengan temuan Wahid Institute (2023) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor kunci dalam penyebaran hoaks adalah absennya sikap kritis dan kebiasaan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Lebih lanjut, Azra (2020) mengungkapkan bahwa konsep isnad (rantai transmisi keilmuan) yang dipertahankan dalam tradisi pesantren sebagaimana diajarkan KH. Hasyim Asy’ari, memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan verifikasi sumber di era digital.
Menurut survei yang dilakukan oleh Masaid dan Rachmawati (2022), 78% responden muslim mengakui bahwa nilai-nilai etika keilmuan dalam tradisi Islam, seperti yang diajarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari, berpotensi mencegah penyebaran disinformasi jika diterapkan dalam perilaku bermedia sosial. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengaktualisasikan pemikiran beliau tentang etika keilmuan dalam konteks digital.
Komitmen terhadap Tradisi dan Kearifan Lokal
Salah satu ciri khas pemikiran KH. Hasyim Asy’ari adalah kuatnya komitmen terhadap preservasi tradisi dan kearifan lokal. Beliau mengajarkan pentingnya memelihara kontinuitas tradisi ulama (turats) yang telah teruji oleh waktu dan terbukti membawa kemaslahatan bagi umat (Bruinessen, 2015). Menurut Ishomuddin (2019), pendekatan KH. Hasyim Asy’ari dalam menyikapi tradisi lokal adalah dengan mengintegrasikannya dalam kerangka ajaran Islam, bukan menolaknya secara frontal.
Dalam era digital yang ditandai oleh globalisasi dan homogenisasi budaya, pemikiran ini menjadi benteng pertahanan identitas umat. Fealy dan Hooker (2019) menjelaskan bahwa fenomena globalisme digital telah menciptakan apa yang disebut sebagai “krisis identitas” di kalangan generasi muda muslim, di mana terjadi ketercerabutan dari akar budaya dan tradisi. Rizal dan Hasan (2021) menambahkan bahwa adopsi nilai-nilai global tanpa filter kritis sering kali berujung pada hilangnya kekhasan dan keunikan identitas lokal.
Tradisi-tradisi yang diperjuangkan KH. Hasyim Asy’ari, seperti tahlilan, manaqiban, dan haul, bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga merupakan media dakwah dan penguatan jati diri (Miftahuddin, 2020). “Tradisi-tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan kultural yang kompleks yang berfungsi sebagai perekat sosial dan media transmisi nilai-nilai Islam yang telah diinkulturasikan,” papar Woodward (2017, p. 112).
Digitalisasi konten dakwah berbasis tradisi menjadi langkah strategis dalam mengaktualisasikan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari di era digital. Menurut studi yang dilakukan oleh Jurdi dan Rahmawati (2021), konten-konten media sosial yang mengangkat tradisi Islam Nusantara memiliki daya tarik yang signifikan bagi generasi milenial dan Gen Z. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan psikologis untuk menemukan akar identitas di tengah arus globalisasi. Suyitno dan Mahfudz
(2022) mendeskripsikan fenomena “neo-tradisionalisme digital” sebagai bentuk aktualisasi tradisi dalam ruang maya. Fenomena ini menjadi bukti relevansi pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang pentingnya memelihara tradisi di tengah gempuran modernitas.

Moderatisme dan Toleransi
KH. Hasyim Asy’ari dikenal sebagai peletak dasar pemikiran Islam moderat (wasathiyyah) di Indonesia. Sikap moderatisme beliau tercermin dalam berbagai fatwa dan pemikiran yang menekankan pada keseimbangan, keadilan, dan penolakan terhadap ekstremisme (Muhtadi, 2020). Menurut Barton (2019), moderatisme KH. Hasyim Asy’ari berakar pada pemahaman mendalam tentang tradisi Islam klasik yang diintegrasikan dengan kesadaran akan konteks sosio- kultural Indonesia.
Dalam konteks dunia digital yang sering diwarnai oleh polarisasi, ujaran kebencian, dan ekstremisme, pendekatan moderat KH. Hasyim Asy’ari menjadi sangat relevan. Nadirsyah dan Fenton (2021) mencatat bahwa algoritma media sosial yang cenderung menciptakan ruang gema (echo chamber) telah memperkuat sikap ekstremisme dan intoleransi di kalangan pengguna internet.
Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari mendorong Islam yang damai, santun, dan mampu bersanding dengan budaya setempat. Beliau menekankan konsep tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), ta’adul (keseimbangan), dan tawazun (keharmonisan) dalam beragama (Zamzami, 2018). Nilai-nilai ini menjadi inspirasi bagi para da’i dan netizen muslim untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin di platform digital.
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2022), 63% konten keagamaan di media sosial Indonesia cenderung mengarah pada pandangan yang eksklusif dan kurang toleran. Di sisi lain, Wahid Foundation (2023) melaporkan bahwa konten-konten yang mengangkat nilai-nilai moderat Islam Nusantara memiliki tingkat interaksi dan engagement yang lebih rendah dibandingkan konten-konten yang sensasional dan cenderung ekstrem.
Tantangan utama Islam moderat di era digital adalah menyajikan nilai moderasi dengan cara menarik yang sesuai algoritma media sosial (Rahman dan Yusuf, 2022). Dalam hal ini, aktualisasi pemikiran KH. Hasyim Asy’ari perlu disertai dengan strategi komunikasi digital yang efektif.
Beberapa inisiatif seperti “Moderasi Beragama Digital” yang diusung oleh Kementerian Agama dan gerakan “Islam Digital Ramah” yang diinisiasi oleh pegiat media sosial merupakan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moderatisme KH. Hasyim Asy’ari di ruang digital (Syam & Nurish, 2021). Inisiatif-inisiatif ini menjadi bukti relevansi pemikiran beliau dalam menjawab tantangan ekstremisme di era digital.
Pendidikan Berbasis Akhlak dan Karakter
Dalam sistem pendidikan yang dibangun oleh KH. Hasyim Asy’ari memandang bahwa pendidikan sejati tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak mulia (Zarkasyi, 2020). Menurut Madjid (2019), sistem pendidikan pesantren yang dikembangkan KH. Hasyim Asy’ari memiliki keunggulan dalam aspek pembentukan karakter dibandingkan sistem pendidikan formal yang lebih menekankan pada aspek kognitif.
Di era digital, pendidikan formal seringkali lebih menekankan aspek teknologi dan keterampilan praktis, sementara dimensi akhlak dan karakter kurang mendapatkan perhatian. Fenomena ini, menurut Lie dan Prasasti (2020), telah menghasilkan generasi yang cakap secara teknis namun rentan secara moral dan etis. Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang pendidikan berbasis akhlak menjadi relevan untuk mendorong integrasi antara kecanggihan teknologi dengan akhlak mulia. Menurut Rahardjo dan Saidi (2021), konsep ta’dib (pendidikan berbasis adab) yang diusung oleh KH. Hasyim Asy’ari dapat menjadi pondasi filosofis bagi pengembangan model pendidikan yang menyeimbangkan aspek teknologi dan akhlak.
Digitalisasi kurikulum pesantren dan pengembangan platform pendidikan berbasis akhlak menjadi langkah konkret dalam mengaktualisasikan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari di era digital. Inisiatif seperti “Pesantren Digital” yang menggabungkan tradisi pesantren dengan keterampilan digital telah menunjukkan hasil yang positif dalam menyiapkan santri untuk menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan jati diri (Muhajir & Rahmat, 2023).
Studi yang dilakukan oleh Tim Peneliti Balitbang Kemenag (2022) menunjukkan bahwa lulusan dari program-program pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dengan keterampilan digital memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap konten-konten negatif di internet dan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk terlibat dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Kemandirian dan Keteguhan dalam Prinsip
Salah satu aspek yang menonjol dari kepribadian KH. Hasyim Asy’ari adalah kemandirian dalam berpikir dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip. Hal ini tercermin dalam sikap beliau yang tegas menolak tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda, meskipun harus menghadapi tekanan dan ancaman (Latief, 2019). Resolusi Jihad yang beliau keluarkan pada 22 Oktober 1945 menunjukkan keberanian dan keteguhan sikapnya dalam membela kemerdekaan Indonesia (Bizawie, 2018).
Di era digital yang ditandai oleh derasnya arus informasi dan opini, sikap mandiri dan teguh dalam prinsip menjadi sangat penting. Menurut Ahmad dan Baihaki (2020), fenomena “terkoneksi tapi terisolasi” (connected but isolated) telah menciptakan kondisi di mana individu semakin rentan terhadap pengaruh eksternal, terutama melalui algoritma media sosial yang memperkuat bias konfirmasi.
“Kemandirian berpikir yang ditunjukkan oleh KH. Hasyim Asy’ari mengajarkan pentingnya sikap kritis dan independen dalam menerima informasi,” tulis Fuad dan Anam (2021, p. 98). Pandangan ini sejalan dengan temuan Komisi Penyiaran Indonesia (2022) yang melaporkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan mandiri merupakan faktor kunci dalam mencegah seseorang termakan hoaks dan propaganda.
Netizen perlu dididik untuk tidak mudah termakan hoaks, propaganda, atau berita yang menyesatkan. Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang pentingnya tabayyun (verifikasi) dan tatsabbut (kehati-hatian) dalam menerima informasi menjadi pondasi untuk membangun masyarakat digital yang cerdas dan berprinsip (Mahfudz, 2021). “Gerakan Literasi Digital” yang diusung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan “Santri Anti-Hoaks” yang digagas oleh komunitas pesantren merupakan implementasi dari nilai-nilai kemandirian dan keteguhan prinsip yang diajarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari (Nugraha & Saefullah, 2023). Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa pemikiran beliau tetap relevan dalam konteks masyarakat digital.
Peran Ulama sebagai Pewaris Nabi
Dalam kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim, KH. Hasyim Asy’ari menekankan bahwa ulama adalah pewaris para nabi (warasat al-anbiya). Konsep ini membawa implikasi bahwa ulama memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pencerahan dan bimbingan kepada umat (Rifai, 2019). Menurut Dhofier (2018), KH. Hasyim Asy’ari memandang bahwa seorang ulama harus memenuhi kualifikasi dalam tiga aspek: keilmuan, amal, dan akhlak.
Dalam konteks digital, peran ulama sebagai pewaris nabi menghadapi tantangan sekaligus peluang yang baru. Hadirnya media sosial dan platform digital telah mengubah lanskap dakwah dan transmisi nilai-nilai keagamaan. Hal ini termasuk dalam hal demokratisasi otoritas keagamaan (Hefner dan Sholikin, 2021).
Para ulama dituntut untuk melek teknologi agar mampu menjangkau umat melalui platform yang digunakan oleh masyarakat modern. Dakwah digital, podcast keislaman, dan kanal YouTube santri adalah media baru yang bisa menjadi ladang amal dan edukasi sebagaimana semangat yang diwariskan KH. Hasyim Asy’ari (Mukaffa, 2022).
Studi yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta (2023) menunjukkan bahwa 72% responden generasi milenial dan Gen Z lebih sering mengakses konten keagamaan melalui platform digital dibandingkan melalui kajian tatap muka. Ini menunjukkan urgensi bagi para ulama untuk mengadaptasi metode dakwah mereka sesuai dengan tren dan kebutuhan zaman.
Beberapa inisiatif seperti “Pesantren Digital” yang didirikan oleh alumni pesantren Tebuireng dan “Ulama Digital” yang diinisiasi oleh PBNU merupakan upaya untuk mengaktualisasikan konsep warasat al-anbiya dalam konteks digital (Nasir & Maimun, 2022). Inisiatif-inisiatif ini menjadi bukti bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang peran ulama masih relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks kekinian.
Persatuan Umat dan Cinta Tanah Air
KH. Hasyim Asy’ari merupakan pelopor semangat nasionalisme dalam bingkai keislaman. Beliau menegaskan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman (hubbul wathan minal iman) dan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama (Burhanudin, 2019). Fatwa beliau mengenai kewajiban bela negara menjadi bukti kecintaan beliau kepada tanah air dan komitmennya terhadap persatuan bangsa.
Dalam era digital, semangat nasionalisme dan persatuan umat menghadapi tantangan berupa fragmentasi sosial dan sektarianisme yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Menurut penelitian Heryanto dan Mutaqin (2021), algoritma media sosial yang cenderung mengelompokkan pengguna berdasarkan minat dan preferensi telah menciptakan “silo-silo” sosial yang memperkuat stereotip dan prasangka antarkelompok.
Platform digital seharusnya berperan dalam menciptakan persatuan (Abdillah dan Rahman, 2020). Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang persatuan umat (ukhuwah) dan cinta tanah air dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ruang digital dari ancaman radikalisme, disinformasi, dan perpecahan bangsa.
Konsep ukhuwah yang diusung oleh KH. Hasyim Asy’ari mencakup tiga dimensi: ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia) (Mujib, 2020). Ketiga dimensi ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat digital yang inklusif dan harmonis.
Inisiatif seperti “Bhinneka Digital” yang diusung oleh BNPT dan “Indonesia Damai Digital” yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan implementasi dari nilai-nilai persatuan dan cinta tanah air yang diajarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari (Syukur & Ramli, 2023). Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa pemikiran beliau tentang persatuan dan nasionalisme tetap relevan dalam konteks digital.
Kesimpulan dan Saran
Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan era digital. Nilai-nilai etika keilmuan, moderatisme Islam, pendidikan berbasis akhlak, komitmen terhadap tradisi, kemandirian berpikir, konsep ulama sebagai pewaris nabi, dan semangat persatuan umat yang beliau ajarkan menawarkan solusi komprehensif atas berbagai permasalahan digital seperti penyebaran hoaks, polarisasi masyarakat, ekstremisme daring, dan krisis identitas. Kekuatan pemikiran beliau terletak pada keseimbangan antara keteguhan dalam prinsip dan keterbukaan terhadap perkembangan zaman, yang memungkinkan aktualisasi ajarannya dalam konteks yang terus berubah.
Untuk mengaktualisasikan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari di era digital, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lembaga pendidikan, terutama pesantren, perlu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum tanpa mengorbankan nilai-nilai adab dan akhlak. Para ulama dan tokoh agama dituntut untuk beradaptasi dengan platform digital sebagai medan dakwah baru, sementara tetap menjaga otentisitas dan kedalaman ajaran. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam mempromosikan konten-konten digital yang mendukung moderatisme, toleransi, dan persatuan bangsa, serta mengembangkan kebijakan yang mendorong ekosistem digital yang sehat.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi metodologi spesifik dalam menerjemahkan konsep-konsep KH. Hasyim Asy’ari ke dalam praktik digital kontemporer. Studi interdisipliner yang menggabungkan pemikiran Islam tradisional dengan ilmu komunikasi, psikologi sosial, dan teknologi informasi akan sangat bermanfaat dalam menghasilkan model-model implementasi yang efektif. Selain itu, dokumentasi dan diseminasi praktik-praktik terbaik dari inisiatif yang telah ada perlu diperkuat untuk memfasilitasi pembelajaran bersama dan replikasi keberhasilan di berbagai konteks. Melalui upaya-upaya ini, warisan intelektual KH. Hasyim Asy’ari dapat menjadi jembatan yang kokoh menghubungkan dua zaman, memandu generasi muslim dalam menavigasi kompleksitas dunia digital tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai keislaman yang fundamental.
Esai ini ditulis oleh Kyai Bey Arifin (Wakil ketua PC IKAPETE Jombang, Wakil ketua Bidang Kajian Pemikiran Hadrotussyeh KH Hasyim Asy’ari).